Jadi, beginilah semuanya berakhir. Apa yang terus hanyalah kenangan. Sebuah jejak yang kian lama kian terhapus. Tapi sekarang, mataku masih melihat wajah, tubuh, dan gerak-gerikmu. Telingaku masih mendengar candamu. Sebab waktu belum mengembalikan apa yang telah diambilnya.
Dua orang anak bermain bola di halaman rumah itu. Halaman dengan pohon jambu yang berbuah lebat. Seorang ibu menggendong anaknya di teras rumah. Suaminya membaca koran di kursi di sampingnya.
“Kenapa senyum?” tanyanya.
Aku berpaling dari jendela kereta dan menatap wajahnya.
“Tidak apa-apa,” kataku tanpa melepas senyum.
“Kok tahu aku tersenyum?” tanyaku.
Dia menunjuk ke kaca jendela.
“Kaca memang material yang meneruskan cahaya. Tapi, kadang ia memantulkan sedikit cahaya jika cahaya itu datang pada sudut yang tepat. Senyum kamu dipantulkan cahaya itu ke mataku,” katanya lucu.
“Ya…ya,” ujarku. “Aku tidak lupa kamu mahasiswa Fisika.”
Dia tertawa kecil.
“Beda kaca dengan cermin yaitu …”
“Tidak tertarik,” kataku memotong. “Terima kasih.”
Kami berdua tertawa.
Namanya Ridha. Dia kuliah di Bandung dan aku bertemu dengannya dalam sebuah perjalanan kereta menuju Jakarta. Aku tak pernah berkenalan dengan seorang yang tergila-gila pada Fisika sebelumnya. Kadang, orang seperti itu mungkin saja menarik. Tapi Ridha, dia begitu menjengkelkan. Setidaknya itulah kesan pertama yang kudapat. Ia kaku dan membosankan.
“Kamu pasti menganggap aku membosankan dan terlalu kaku. Iya, kan?” tanyanya.
“Persis,” kataku.
“Jangan bohong,” katanya.
Aku tersenyum dalam hati.
“Kali ini sayangnya aku jujur,” kataku.
Seorang pelayan menawarkan makanan kepadaku. Aku menggeleng sambil mengucapkan terima kasih.
“Apa itu di tanganmu?” tanya Ridha.
“Surat.”
“Surat cinta?”
“Surat benci.”
Dia mengerutkan kening sambil memonyongkan bibirnya.
“Apa begitu cara mahasiswa Fisika mengekspresikan ketidakmengertiannya?” tanyaku. “Mengerutkan kening sambil monyong.”
“Setidaknya ekspresi itu berhasil memberi tahu kamu aku tidak mengerti.”
“Tak perlu sekonyol itu.”
“Yang penting efektif,” katanya tidak mau kalah.
“Kamu orangnya tidak mau kalah, ya?” tanyaku.
“Apa itu surat benci?”
Sebuah percakapan seharusnya mengalir. Tidak didominasi dan diarahkan oleh seseorang. Lalu, apa yang harus aku bincangkan dengan orang semacam ini?
“Mengapa diam?” tanyanya.
“Kamu tidak perlu tahu!” bentakku.
Dia diam
Kereta melintas terowongan dan aku cepat-cepat menutup jendela kereta.
Jadi, apa artinya sebuah rindu? Apa artinya memiliki sebuah rindu? Jika semuanya berakhir dengan semena-mena. Ini tanganku. Banyak yang dapat kulakukan dengan kedua tanganku. Jika aku hebat, aku bahkan dapat mengubah dunia dengan kedua tanganku. Menghancurkannya malah. Tapi rindu ini? Tak ada yang bisa aku lakukan. Bahkan memindahkan gunung pun masih mungkin. Lebih mungkin dari mengobati rasa rindu ini. Lalu, mengapa memilikinya? Menginginkannya? Memendamnya? Rindu adalah jalan menuju kenangan. Sekaligus lari dari kenyataan.
“Kamu sedang sedih, ya?” tanyanya.
“Apa aku kelihatan sedih?” tanyaku dengan nada sebal.
“Setidaknya kamu membawa surat benci itu di tanganmu. Biasanya sesuatu yang menyedihkan juga sekaligus menyebalkan dan kamu kelihatan sedang sebal.”
“Aku sebal sama kamu.”
“Kenapa? Apakah aku yang menulis surat benci itu?”
Bayangkan logika yang dipakainya! Seorang mahasiswa Fisika seharusnya memiliki pikiran yang runtut. Tidak berpikir dengan logika yang loncat-loncat seperti itu.
“Aku memang sengaja bicara dengan logika yang meloncat-loncat!” katanya.
“Bodoh!”
“Untuk melucu. Agar kamu tidak sedih.”
“Aku tidak sedih,” bentakku. “Dan kamu tidak lucu sama sekali.”
Dia diam.
Namanya Ridha. Mahasiswa fisika itu. Yang rambutnya ikal. Kacamata tebal. Kulitnya sawo matang dan giginya hitam kena nikotin. Yang tinggi dan kurus itu. Aku akui, dia unik. Sebuah dunia yang beda. Aku seperti seorang petualang menatap matanya. Terra incognito.
“Kamu suka puisi?” tanyanya.
“Tidak,” kataku.
“Pernah dengar nama Roger McGough?”
“Siapa? Pasti penyair.”
“Mau dengar puisinya? Aku bawa bukunya.”
“Jangan yang romantis. Puisi romantis itu gombal.”
Dia tidak menghiraukanku.
“Judulnya vinegar. Begini bunyinya:
“Sometimes
I feel like a priest
In a fish & chip queue
Quietly thinking
As the vinegar runs through
How nice it would be
To buy supper for two
“Atau pernah dengar nama Adrian Henri? Begini puisinya
“A nun in a supermarket
Standing in the queue
Wondering what it’s like
To buy groceries for two“
Aku diam.
“Tahu apa judul puisi barusan? Poem for Roger Mc Gough,” katanya dengan penuh kepuasan.
Aku menangis. Jadi, beginilah akhirnya. Aku menangis sendirian di sebuah kereta. Mengenang dirimu. Aku tahu, akhirnya semua akan terlupakan. Tapi, aku tak ingin melupakannya. Melupakanmu adalah mengingat rasa sakit ini.
“Kamu pernah membenci seseorang?” tanyanya.
“Pernah,” jawabku sambil mengusap air mata.
“Alasannya?”
“Karena aku mencintainnya.”
“Aku tak pernah membenci seseorang karena mencintainya.”
“Aku benci karena dia meninggalkanku,” ucapku.
“Dia mencintai kamu?”
“Sangat.”
“Aku tak akan pernah meninggalkan seseorang yang sangat aku cintai.”
“Dia tak punya pilihan.”
“Dia selalu punya pilihan.”
“Dia pasti memilih untuk tinggal jika dia bisa memilih.”
Dia diam beberapa saat.
“Aku pun begitu,” katanya kepada diri sendiri. “Aku pasti memilih untuk tinggal jika aku bisa memilih.”
Jadi, memang seperti itulah adanya. Dia tak memiliki pilihan. Tapi, dia tak akan memilih jika pilihannya membuat dia tak punya pilihan. Tapi, dia telah memilih dan dia akhirnya tak memiliki pilihan. Aku pun tak memiliki pilihan. Dia telah memilih dan aku pun tak memiliki pilihan. Tapi, aku masih memiliki kekuatan untuk menghilangkan akibat dari ketiadaan pilihan itu. Meski aku tak merasa memiliki kekuatan untuk memilih menghilangkan akibat itu. Atau aku sebenarnya telah memilih untuk tak menghilangkan akibat itu?
“Kamu percaya takdir?” tanyanya.
Aku mengangguk.
“Kamu tidak?” tanyaku.
“Aku percaya setiap orang akan mati,” katanya.
“Bukan suatu pilihan, itulah takdir,” lanjutnya.
Aku mengangguk setuju.
Jadi, semuanya ini takdir.
“Iya,”sahutnya. “Semua ini takdir.”
Namanya Ridha. Jika kematian dapat kita lihat sebelumnya, alangkah mudah untuk memilih. Tapi, kematian begitu dingin, begitu diam. Dia tak berkata apa-apa. Dia tak mengisyaratkan apa-apa.
Kereta melintas cepat di atas rumah-rumah. Senja merah mewarnai langit. Tiang-tiang listrik berlarian dan suara adzan maghrib terdengar melesat datang lalu pergi. Dia selalu mengenggam tanganku saat aku menangis. Dia tak akan memelukku karena dia takut aku tak suka dipeluk. Aku suka dipeluk saat menangis hanya dia tak pernah tahu. Satu hari dia datang membawa sebuah kerang yang biasa dipakai untuk bermain congklak. Dia menaruhnya di depanku dan aku tak bereaksi apa-apa. Dia tak pernah memberiku sesuatu yang berharga. Tapi, dia selalu memberiku sesuatu yang unik. Begitulah dia menciptakan rindu yang ada di hatiku kini dengan kejamnya.
Kereta melambat. Hampir sampai Gambir. Kumasukkan buku puisi Roger Mc Gough dan Adrian Henri ke dalam tasku. Aku ingin membuang surat yang ada di tanganku ini. Tapi, aku masih ingin menyiksa diriku dengan rindu yang dapat diciptakannya. Maaf Ridha, aku bercanda. Ini sama sekali bukan surat benci. Aku kini tak menyesali keunikan dirimu. Mengirimiku surat ketika teknologi begitu canggih? Jika kau masih hidup, entah apa lagi kejutan yang akan kau berikan kepadaku.
Dua orang anak bermain bola di halaman rumah itu. Halaman dengan pohon jambu yang berbuah lebat. Seorang ibu menggendong anaknya di teras rumah. Suaminya membaca koran di kursi di sampingnya.
“Kenapa senyum?” tanyanya.
Aku berpaling dari jendela kereta dan menatap wajahnya.
“Tidak apa-apa,” kataku tanpa melepas senyum.
“Kok tahu aku tersenyum?” tanyaku.
Dia menunjuk ke kaca jendela.
“Kaca memang material yang meneruskan cahaya. Tapi, kadang ia memantulkan sedikit cahaya jika cahaya itu datang pada sudut yang tepat. Senyum kamu dipantulkan cahaya itu ke mataku,” katanya lucu.
“Ya…ya,” ujarku. “Aku tidak lupa kamu mahasiswa Fisika.”
Dia tertawa kecil.
“Beda kaca dengan cermin yaitu …”
“Tidak tertarik,” kataku memotong. “Terima kasih.”
Kami berdua tertawa.
Namanya Ridha. Dia kuliah di Bandung dan aku bertemu dengannya dalam sebuah perjalanan kereta menuju Jakarta. Aku tak pernah berkenalan dengan seorang yang tergila-gila pada Fisika sebelumnya. Kadang, orang seperti itu mungkin saja menarik. Tapi Ridha, dia begitu menjengkelkan. Setidaknya itulah kesan pertama yang kudapat. Ia kaku dan membosankan.
“Kamu pasti menganggap aku membosankan dan terlalu kaku. Iya, kan?” tanyanya.
“Persis,” kataku.
“Jangan bohong,” katanya.
Aku tersenyum dalam hati.
“Kali ini sayangnya aku jujur,” kataku.
Seorang pelayan menawarkan makanan kepadaku. Aku menggeleng sambil mengucapkan terima kasih.
“Apa itu di tanganmu?” tanya Ridha.
“Surat.”
“Surat cinta?”
“Surat benci.”
Dia mengerutkan kening sambil memonyongkan bibirnya.
“Apa begitu cara mahasiswa Fisika mengekspresikan ketidakmengertiannya?” tanyaku. “Mengerutkan kening sambil monyong.”
“Setidaknya ekspresi itu berhasil memberi tahu kamu aku tidak mengerti.”
“Tak perlu sekonyol itu.”
“Yang penting efektif,” katanya tidak mau kalah.
“Kamu orangnya tidak mau kalah, ya?” tanyaku.
“Apa itu surat benci?”
Sebuah percakapan seharusnya mengalir. Tidak didominasi dan diarahkan oleh seseorang. Lalu, apa yang harus aku bincangkan dengan orang semacam ini?
“Mengapa diam?” tanyanya.
“Kamu tidak perlu tahu!” bentakku.
Dia diam
Kereta melintas terowongan dan aku cepat-cepat menutup jendela kereta.
Jadi, apa artinya sebuah rindu? Apa artinya memiliki sebuah rindu? Jika semuanya berakhir dengan semena-mena. Ini tanganku. Banyak yang dapat kulakukan dengan kedua tanganku. Jika aku hebat, aku bahkan dapat mengubah dunia dengan kedua tanganku. Menghancurkannya malah. Tapi rindu ini? Tak ada yang bisa aku lakukan. Bahkan memindahkan gunung pun masih mungkin. Lebih mungkin dari mengobati rasa rindu ini. Lalu, mengapa memilikinya? Menginginkannya? Memendamnya? Rindu adalah jalan menuju kenangan. Sekaligus lari dari kenyataan.
“Kamu sedang sedih, ya?” tanyanya.
“Apa aku kelihatan sedih?” tanyaku dengan nada sebal.
“Setidaknya kamu membawa surat benci itu di tanganmu. Biasanya sesuatu yang menyedihkan juga sekaligus menyebalkan dan kamu kelihatan sedang sebal.”
“Aku sebal sama kamu.”
“Kenapa? Apakah aku yang menulis surat benci itu?”
Bayangkan logika yang dipakainya! Seorang mahasiswa Fisika seharusnya memiliki pikiran yang runtut. Tidak berpikir dengan logika yang loncat-loncat seperti itu.
“Aku memang sengaja bicara dengan logika yang meloncat-loncat!” katanya.
“Bodoh!”
“Untuk melucu. Agar kamu tidak sedih.”
“Aku tidak sedih,” bentakku. “Dan kamu tidak lucu sama sekali.”
Dia diam.
Namanya Ridha. Mahasiswa fisika itu. Yang rambutnya ikal. Kacamata tebal. Kulitnya sawo matang dan giginya hitam kena nikotin. Yang tinggi dan kurus itu. Aku akui, dia unik. Sebuah dunia yang beda. Aku seperti seorang petualang menatap matanya. Terra incognito.
“Kamu suka puisi?” tanyanya.
“Tidak,” kataku.
“Pernah dengar nama Roger McGough?”
“Siapa? Pasti penyair.”
“Mau dengar puisinya? Aku bawa bukunya.”
“Jangan yang romantis. Puisi romantis itu gombal.”
Dia tidak menghiraukanku.
“Judulnya vinegar. Begini bunyinya:
“Sometimes
I feel like a priest
In a fish & chip queue
Quietly thinking
As the vinegar runs through
How nice it would be
To buy supper for two
“Atau pernah dengar nama Adrian Henri? Begini puisinya
“A nun in a supermarket
Standing in the queue
Wondering what it’s like
To buy groceries for two“
Aku diam.
“Tahu apa judul puisi barusan? Poem for Roger Mc Gough,” katanya dengan penuh kepuasan.
Aku menangis. Jadi, beginilah akhirnya. Aku menangis sendirian di sebuah kereta. Mengenang dirimu. Aku tahu, akhirnya semua akan terlupakan. Tapi, aku tak ingin melupakannya. Melupakanmu adalah mengingat rasa sakit ini.
“Kamu pernah membenci seseorang?” tanyanya.
“Pernah,” jawabku sambil mengusap air mata.
“Alasannya?”
“Karena aku mencintainnya.”
“Aku tak pernah membenci seseorang karena mencintainya.”
“Aku benci karena dia meninggalkanku,” ucapku.
“Dia mencintai kamu?”
“Sangat.”
“Aku tak akan pernah meninggalkan seseorang yang sangat aku cintai.”
“Dia tak punya pilihan.”
“Dia selalu punya pilihan.”
“Dia pasti memilih untuk tinggal jika dia bisa memilih.”
Dia diam beberapa saat.
“Aku pun begitu,” katanya kepada diri sendiri. “Aku pasti memilih untuk tinggal jika aku bisa memilih.”
Jadi, memang seperti itulah adanya. Dia tak memiliki pilihan. Tapi, dia tak akan memilih jika pilihannya membuat dia tak punya pilihan. Tapi, dia telah memilih dan dia akhirnya tak memiliki pilihan. Aku pun tak memiliki pilihan. Dia telah memilih dan aku pun tak memiliki pilihan. Tapi, aku masih memiliki kekuatan untuk menghilangkan akibat dari ketiadaan pilihan itu. Meski aku tak merasa memiliki kekuatan untuk memilih menghilangkan akibat itu. Atau aku sebenarnya telah memilih untuk tak menghilangkan akibat itu?
“Kamu percaya takdir?” tanyanya.
Aku mengangguk.
“Kamu tidak?” tanyaku.
“Aku percaya setiap orang akan mati,” katanya.
“Bukan suatu pilihan, itulah takdir,” lanjutnya.
Aku mengangguk setuju.
Jadi, semuanya ini takdir.
“Iya,”sahutnya. “Semua ini takdir.”
Namanya Ridha. Jika kematian dapat kita lihat sebelumnya, alangkah mudah untuk memilih. Tapi, kematian begitu dingin, begitu diam. Dia tak berkata apa-apa. Dia tak mengisyaratkan apa-apa.
Kereta melintas cepat di atas rumah-rumah. Senja merah mewarnai langit. Tiang-tiang listrik berlarian dan suara adzan maghrib terdengar melesat datang lalu pergi. Dia selalu mengenggam tanganku saat aku menangis. Dia tak akan memelukku karena dia takut aku tak suka dipeluk. Aku suka dipeluk saat menangis hanya dia tak pernah tahu. Satu hari dia datang membawa sebuah kerang yang biasa dipakai untuk bermain congklak. Dia menaruhnya di depanku dan aku tak bereaksi apa-apa. Dia tak pernah memberiku sesuatu yang berharga. Tapi, dia selalu memberiku sesuatu yang unik. Begitulah dia menciptakan rindu yang ada di hatiku kini dengan kejamnya.
Kereta melambat. Hampir sampai Gambir. Kumasukkan buku puisi Roger Mc Gough dan Adrian Henri ke dalam tasku. Aku ingin membuang surat yang ada di tanganku ini. Tapi, aku masih ingin menyiksa diriku dengan rindu yang dapat diciptakannya. Maaf Ridha, aku bercanda. Ini sama sekali bukan surat benci. Aku kini tak menyesali keunikan dirimu. Mengirimiku surat ketika teknologi begitu canggih? Jika kau masih hidup, entah apa lagi kejutan yang akan kau berikan kepadaku.

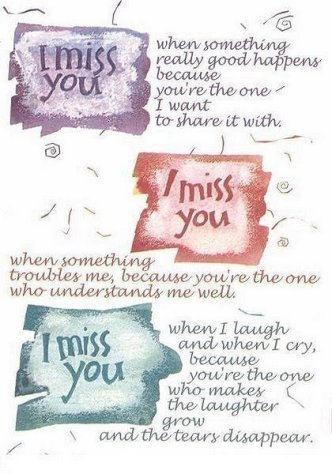




















No comments:
Post a Comment